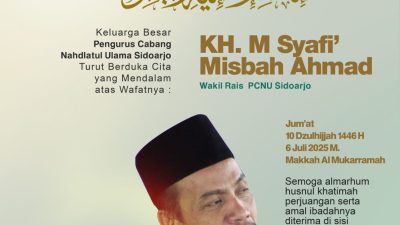Nahdlatul Ulama (NU) (menurut catatan) sebagai kumpulan ulama pondok pesantren yang memegang teguh ajaran ahlusunnah wal jama’ah, empat mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali), dalam aqidah memegang dua mazhab Abu Hasan Al Asy’ari dan Abu Manshur Al Maturidi, serta dua mazhab tasawuf Junaidi Al Baghdadi dan Abu Hamid Al Ghazali. Didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926 (PBNU, 2014). Terdapat faktor internal dan eksternal faktor yang menjadi kondisi objektif sekaligus melatar belakangi berdirinya NU. Secara sekilas faktor internal menghadapi situasi kolonialisme, dan eksternal tata dunia global yang sedang mengalami perang dunia serta dunia Islam menghadapi ancaman terhadahap kekuatan wahabi. Yang terakhir lahirlah Komite Hejaz (Choirul Anam, 1985).
Berdirinya NU adalah penanda dari realitas atau respon atas kondisi objektif seperti kalimat di atas, sehingga berlangsung perubahan sosial yang sebelumnya tidak ada, yakni hadir(nya) organisasi. Bukankah ini hal yang biasa? Namun setidaknya banyak organisasi yang didirikan setelah itu bubar jalan. Secara teoritik terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat dikarenakan bertemunya titik kulminasi antara kondisi sosial objektif dengan kepentingan aktor subyektif. Ke(hadir)an NU adalah titik perubahan yang mendasar. Mengapa demikian? Seperti apakah aktor penggeraknya yang mampu melihat kondisi sosial objektif itu? Dan apa yang tertinggal dari studi-studi NU selama ini atau alpa dilihat? Di tengah gempuran budaya yang menerpa NU, organisasi ini masih penting dalam konteks sekarang.
Intelektual Publik
Membaca ke(hadir)an NU sering kali linier dan banyak catatan yang tertinggal, terutama di ruang kelas. Banyak narasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negeri ini yang “menghapus” peranan NU. Karena terutama membaca NU ini bersilangan dengan literatur yang jauh dari realitas sehari-hari. NU adalah realitas keseharian masyarakat bawah di negeri ini, yang itu tidak tertangkap oleh teori yang berseliweran di perguruan tinggi. Sehingga aktifitas keseharianya tidak di/terpotret secara utuh. Narasi yang terbaca kemudian aktifitas NU disesuaikan dengan pandangan dan teori di luar NU, itupun yang dinaskahkan adalah satu kegiatan yang memiliki kaitan dengan peristiwa besar dan terkadang direduksi karena peranan elitnya belaka.
Banyak para akademisi kurang mewaspadai teori yang sudah berubah, karena dianggap jauh dari situasi dan dianggap tumpang tindih dengan pascamodernisme (Lloyd, 1994). Tema pusatnya masih berkisar pada tindakan aktor tunggal, yang sebenarnya dalam perspektif Giddens (2011) terdapat dialektika dan saling mempengaruhi antara aktor (agensi) dengan struktur. Inilah yang disebut dengan teori strukturasi, yakni mencakup kemampuan intelektual aktor yang berada pada dimensi spasial dan temporal dalam aksi kesehariannya (Abercrombie, Hill, Turner, 2010). Ini letak kekeliruan mendasar dalam menarasikanke(hadir)an NU pada masa awalnya, memisahkan agen dan struktur.
Bahwa seluruh tindakan sosial membutuhkanstruktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial , pada akhirnya berlangsung proses perubahan sosial dari sebelumnya tidak ada menjadi ada seperti organisasi. Sehingga (tidak salah juga) banyak sekali tokoh NU lokal dan peristiwa-peristiwa lokal tidak di/tertulis dalam sejarah. Celakanya banyak sekali ilmuwan sosial yang membaca NU dari perspektif barat dan non barat. Membaca NU masih Eropa sentris, seperti ungkapan yang dilontarkan oleh J.C. van Leur terhadap perkembangan historiografi kolonial. Jangan melihat kehidupan masyarakat dari atas geladak kapal saja, artinya satu penulisan tentang masyarakat Hindia Belanda hanya dari sudut pandang penguasa saja.
Cara pandang demikian hanya membatasi diri bahwa NU sebatas kumpulan ulama yang ingin melegalkan gerakannya. Seperti historiografi klasik yang bersifat istana sentris, yang melihat pergolakan sosial dari dinamika kraton belaka. Artinya dinamika sosial masyarakat dipisahkan dengan aktor elitnya. Tidak begitu salah bila memotret dari kata Nahdlatul Ulama yang berarti Kebangkitan Ulama, bukan kebangkitan umat. Kesan pertama yang ditangkap hanya bangkitnya elit muslim ingin melakukan perubahan melalui berorganisasi. Padahal jika ditelisik lebih jauh, dalam proses perubahan sosial posisi agensi mampu membaca jiwa zaman (zeitgeis), dan itu datang dari sekelompok orang atau minoritas yang berbeda tindakannya dengan mainstream. Minoritas ini memilih jalannya sendiri, keluar dari pemahaman umum karena mampu membaca serangkaian praktek sosial secara kritis.
Para perinstis dan pendiri NU kala itu tidak bisa dipisahkan elit keraton, yang tentu saja memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Banyak cerita berserakan mereka (Ulama) yang merupakan klas bangsawan.
Cerita tentang Hadratussyech Hasyim Asy’ari merupakan keturunan Sultan Hadiwijaya dan seterusnya. Begitu juga banyak sekali ulama perintis dan pendiri NU lainnya bergelar Raden. Akan tetap para elit bangsawan tersebut kemudian memilih menjadi jalur keilmuan berbasis keagamaan, dan tidak lagi melibatkan diri dalam dinamika klas bangsawan kraton.
Para elit di negeri ini, pada saat itu banyak yang berkelindan dengan kepentingan kolonial dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Ini adalah realitas yang dibaca oleh elit yang memilih jalur pemberdayaan dengan cara mendidik rakyat. Struktur mempengaruhi agensi seperti dalam bahasa Giddens di atas. Mendirikan pesantren dan kemudian mendorong rakyat untuk belajar “menuliskan” ceritanya sendiri. Dikenalkan dengan kalam, diajari berkhidmat dan dituntun mencintai sang khaliq. Adapun caranya pertama-tama, para elit bangsawan yang sudah ‘bermetamorfosis’ menjadi cendikiawan (ulama), bangkit dan mendidik rakyat untuk sadar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya perlawanan terhadap kolonialisme asing, menolak penindasan dan rasa ingin merdeka adalah konsekuensi dari pendidikan para ulama. Karenanya dalam proses pendirian Republik Indonesia menjadi salah satu pionernya dan ikut meletakkan pondasinya.
Pada titik ini, kalangan ulama bisa dinyatakan sebagai intelektual publik. Kumpulan intelektual memiliki tanggung jawab publik. Bukan sebagai ilmuwan yang mandiri yang hanya mengabdi pada kepentingan yang tidak terkait dengan kebutuhan publik atau masyarakat luas. Kerja-kerja NU hari ini setidaknya diletakkan pada tanggung jawab keilmuan yang memiliki tanggung jawab pada publik.
Creative Minority
Sebagaimana sekilas di atas, perubahan sosial tidak bisa dipisahkan antara realitas sosial sebagai strukturnya dan agensi-nya. Keduanya merupakan bagian dari dialektika sistem sosial yang terus menerus. Kendati begitu, tidak semua (mayoritas) agensi sebagai inisiator atau perancang yang bisa berdialetika dengan struktur sosial yang kemudian melakukan perubahan sosial. Adalah sedikit orang yang memiliki kesamaan visi dalam rangka melakukan perubahan sosial. Ini oleh Arnold J Toynbee sejarawan Inggris dalam karyanya A Study of History disebut sebagai creative minority.
Maju dan mundurnya sebuah peradaban lebih ditentukan oleh derajad kemampuan mengelola kekuatan internal oleh agensinya. Kondisi eksternal bukanlah faktor utama penyebab kemunduran suatu sistem sosial (peradaban). Kemampuan creative minority melakukan dialektika dengan struktur sosial, yang berada dalamdimensi spasial dan temporal pada aksi kesehariannya. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh para pendiri NU pada masa awalnya. Kebangkitan para ulama, atau yang kemudian organisasinya dikenal dengan istilah NU ini harus dibaca sebagai kekuatan creative minority. Hadratussyech Hasyim Asy’ari, Kyai Wahab Hasbullah serta Kyai Bisri Sjansuri tidak saja merupakan intelektual publik, tapi juga sebagai kekuatan creative minority yang tidak saja meng(hadir)kan organisasi NU, tapi juga mampu meletakkan pondasi peradaban Islam di negeri ini, di luar peradaban Islam di Timur Tengah. Pertanyaan selanjutnya bisakah itu dikerjakan oleh generasi hari ini dengan tantangan yang lebih berat tentunya.
Kita bisa saksikan dari naskah-naskah masa lalu, tentang kebesaran peradaban besar di dunia, mulai dari Eropa dan benua Amerika bisa dibaca kebesaran. Pun di wilayah Nusantara terdapat Sriwijaya, Majapahit dan lain-lain, yang kesemuanya itu pernah mencapai zaman gemilang. Jejak kegemilangannya bisa disaksikan hingga hari ini. Pertanyaannya penting adalah mengapa hanya bisa jejaknya yang bisa kita baca dan saksikan? Kegagalan kaum creative minority melakukan dialektika dengan struktur sosialnya yang menentukan proses transformasi perjalanan suatu peradaban. Sebagai organisasi, NU sampai hari ini masih bisa melakukan proses transformasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Akhiran
Orientasi penulisan masa lampau tentang NU dan segala macam kisi-kisinya, setidaknya bisa diletakkan pada dua diskursus di atas, sebagai intelectual publik dan creative minority. Kedua diskursus ini tidak semata-mata milik kelas formal dan terjebak pada batas-batas akademik yang kaku. Kadang kala kelas formal memisahkan dirinya dengan tanggung jawab publik dan sudah kesedot dalam pemahaman mayoritas yang itu sudah terkait dengan kepentingan kapital. Daya kreatif dari kelas formal sudah menjadi legitimasi bagi teori yang sudah mapan. Sehingga historiografi yang hadir dalam karya lebih menjelaskan peristiwa yang itu menghilangkan narasi NU sebagai fokus kajian.
Dua diskursus di atas juga bisa menggambarkan dialektika antara agensi dan struktur di level bawah, yang kebanyakan keberadaan aktor-aktor sosial NU ada di bawah. Keberadaan pesantren yang ada di pedesaan secara nyata memberikan sumbangan penting bagi lahirnya tidak saja pendidikan, tapi juga peradaban masyarakatnya. Belum lagi kyai-kyai kampung dan tokoh-tokoh NU lokal yang memiliki sumbangan besar pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun narasinya hilang di tengah “hutan” teori dan motodologi mainstream. Penulisan mengenai pesantren, kyai kampung dan masyarakat santri sekaligus sebagai pengingat bahwa historiografi tidak saja sekedar menarasikan tokoh besar dan peristiwa besar. Dan menulis tentang sejarah NU di lokal-lokal, pesantren, kyai dan masyarakat santri seperti menulis ‘sejarah dari bawah’, meminjam istilah EP Thompson. Syarat utama dari historiografi NU seperti ini harus segera dilakukan. (*)
Rujukan:
Abercrombie, N., Hill, S., & Turner, B. (2010). Kamus Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
AD & ART NU Keputusan Muktamar Ke-34 NU di Lampung
Anam, Choirul 1985, Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama, Solo: Jatayu.
Giddens, A. (2011). The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisa Sosial. Yogyakarta: Pedati
Lloyd, D. 1994, “Ethnic Cultural, Minority Discourse and the State, dalam F. Barker, P. Hulme dan M. Iversen (eds), Colonial Discourse Postcolonial Theory. Manchester: Manchester University Press.