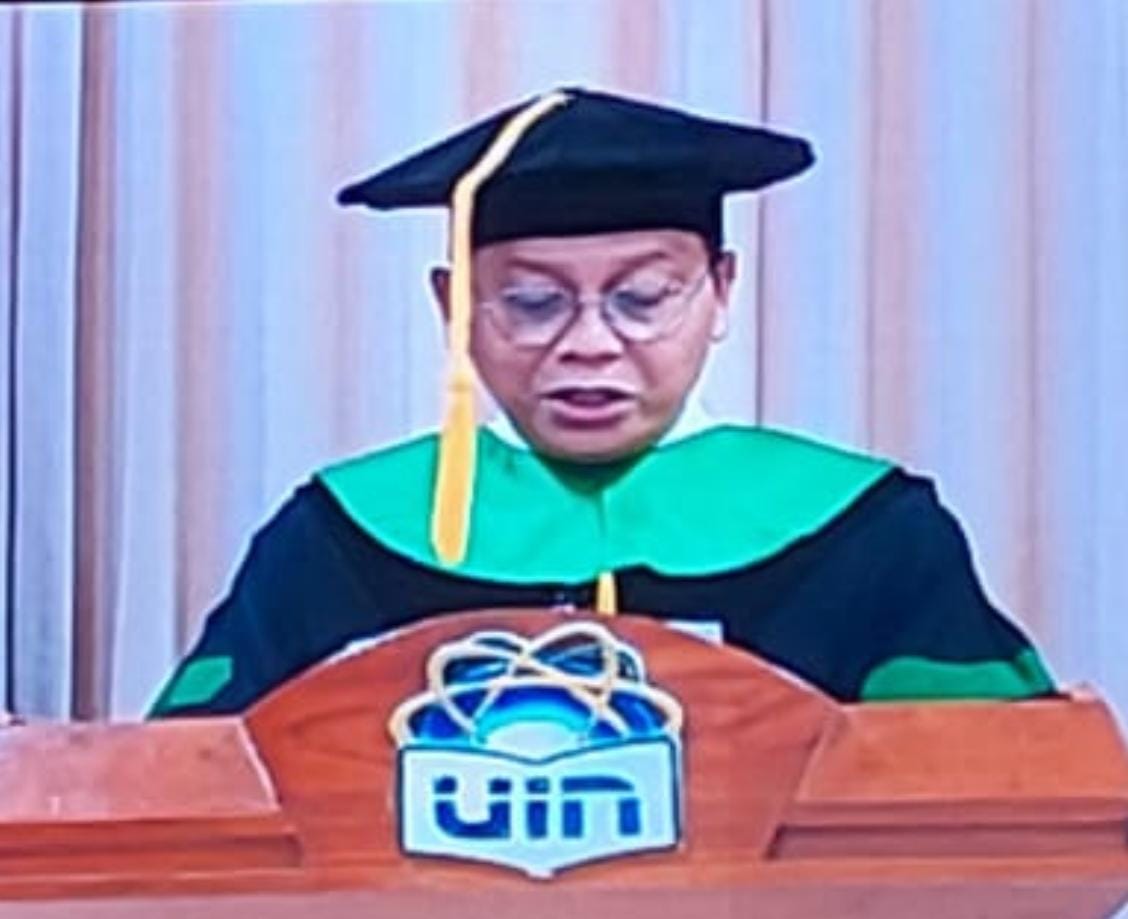Tangerang, jurnal9.tv -Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Dr. Rumadi Ahmad MA pada Rabu (20/12) pagi dikukuhkan sebagai Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Rumadi membacakan pidato pengukuhan berjudul ‘Negosiasi Batas Akomodasi Negara terhadap Agama:
Perspektif Politik Hukum’.
Pada Sidang Senat Terbuka yang berlangsung di Auditorium Harun Nasution ini, UIN Jakarta secara bersamaan mengukuhkan 10 guru besar bidang Agama. Selain Prof Rumadi, nama guru besar yang dikukuhkan adalah Prof Dr JM Muslimin, MA, Prof Dr Abdul Halim MAg, Prof Dr Muhammad Maksum, Prof Syamsul Rijal, Ph.D, Prof Dr Komarusdiana, Prof Dr Fuad Thohari, Prof Dr Asep Syarifudidin Hidayat, Prof Dr Khamami Zada dan Prof Dr Hamka Hasan.
Dalam pidatonya, Rumadi secara khusus mengkaji beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bagian dari politik hukum, terkait persoalan keagamaan, karena pada dasarnya Putusan MK adalah bagian dari politik hukum. Beberapa putusan itu diantaranya terkait UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya soal Poligami dan Status Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan Yang Sah, Nikah Beda Agama dan Pembatasan Usia Perkawinan. Selain itu juga dikaji Keputusan MK tentang Kolom Agama dalam KTP bagi Penghayat Kepercayaan dalam
Uji materi UU Adminduk, Hukum Penodaan Agama
UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 dan Pasal 156a UU KUHP (lama). Rumadi juga mengangkat soal penerapan Hukum Pidana Islam melalui Peradilan Agama
Bagi Rumadi, Indonesia memang bukan negara agama, tapi aspirasi keagamaan tidak mungkin diabaikan begitu saja. Sebagai negara yang mendasarkan dirinya pada prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Indonesia membuka ruang akomodasi aspirasi keagamaan menjadi kebijakan negara. “Pertanyaannya, apakah semua aspirasi keagamaan bisa, bahkan harus diakomodasi melalui kebijakan? Kalau tidak, sampai batas mana akomodasi itu dilakukan?” Ungkapnya.
Dari kajiannya, Rumadi menilai akomodasi negara terhadap agama semakin berkembang luas dan mendalam. Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas masyarakat Indonesia aspirasinya telah banyak terakomodasi. Akomodasi struktural yang pada masa lampau dianggap sebagai kebijakan politik penting, sekarang ini hampir tidak menjadi isu karena semakin banyaknya aktifis Islam dari berbagai latar belakang yang menduduki posisi-posisi penting dalam stuktur birokrasi. “Demikian juga akomodasi legislatif, sejumlah UU dan juga regulasi di bawahnya banyak mengakomodasi kepentingan umat Islam, terutama yang terkait dengan layanan keagamaan, baik layanan ibadah, ekonomi, pendidikan pesantren, industri halal dan sebagainya,” tegasnya.
Akomodasi terhadap aspirasi Islam telah dilakukan hampir dalam semua lini dan bisa membawa dampak ganda. Di satu sisi, membantah narasi bahwa Islam di Indonesia yang dipeluk mayoritas penduduk tapi secara politik terpinggirkan. Namun di sisi lain, arus ini akan menimbulkan politik mayoritarian yang pada level tertentu bisa menimbulkan ketidaknyaman kelompok yang tidak masuk dalam arus tersebut. “Politik mayoritarian, meskipun tidak sampai pada level perubahan dasar negara, namun bisa berimplikasi pada relasi sosial keagamaan, baik pada level nasional maupun lokal,” tambahnya.
Ke depan, Rumadi memprediksi politik posisi agama dalam Negara akan terus berada dalam arena kontestasi. Tidak ada rumusan pasti aspek-aspek keagamaan mana yang bisa masuk dalam regulasi Negara, dan mana yang tidak boleh, kecuali ketidakmungkinan adanya hukum pidana Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan-putusan MK.
Inkonsistensi Penafsiran MK
Terhadap cara penafsiran terhadap konstitusi dan cara memandang persoalan keagamaan, menurut Rumadi putusan MK tidak selalu linier. Dalam hal tertentu MK sangat progresif, tapi dalam hal yang lain cenderung konservatif tanpa mau mempertimbangkan aspek sosial. “Saya setuju dengan apa yang disampaikan Simon Butt yang menyebut Putusan MK terkait dengan persoalan keagamaan tampak ambigu dan inskonsisten,” tegasnya.
Rumadi mencontohkan Putusan MK terkait hukum keluarga, seperti soal nikah beda agama, cenderung konservatif. Tapi terkait dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sangat progresif, sehingga mendapat reaksi negatif dari sejumlah kalangan, termasuk dianggap melegalkan perzinaan. “Tentu saja tudingan ini bantah oleh MK,” sambungnya.
Terkait penerapan hukum pidana Islam, lanjut Rumadi, MK membuat semacam batas akomodasi atau margin of accommodation. MK berpendapat memasukkan hukum pidana Islam dalam kewenangan Pengadilan Agama tidak sesuai dengan paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara agama dan negara. Dengan perpsepktif ini, MK cenderung komservatif menutup pintu kemungkinan adanya hukum pidana yang khusus berlaku bagi umat Islam secara nasional.
Karena itu, negosiasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional lebih pada upaya memasukkan aspek-aspek pidana Islam, yang tidak mudah dilakukan karena harus berurusan banyak perspektif. “Salah satu contohnya, pengaturan mengenai zina yang diadopsi dalam KUHP Baru yang dijadikan sebagai delik aduan, bukan delik biasa sebagaimana pencurian,” tambahnya.
Rumadi menilai transformasi hukum pidana Islam ke dalam peraturan perundang-undangan, lebih merupakan proses ‘Indonesianisasi’ hukum pidana, daripada Islamisasi hukum pidana nasional. “Konsekuensinya, jika proses Indonesianisasi gagal dilakukan, maka dia akan tertolak,” simpulnya. (*)